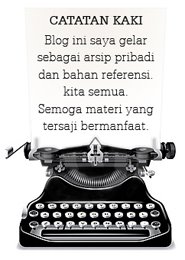Kalori yang mengalir dari satu mata rantai ke mata rantai yang lain itu awalnya berangkat dari setangkai daun –yang dalam arti luas merujuk pada organ, jaringan, atau individu sel tunggal yang berklorofil. Tak ada substansi lain yang bisa memetik energi surya secara langsung, dan kemudian membawanya ke sistem rantai makanan, kecuali daun.
Di dalam sel-sel daun ada mekanisme yang luar biasa pada saat sinar matahari datang menerpa. Dalam tempo hanya sepersekian juta detik, energi foton matahari tadi berpindah posisi, berubah bentuk, menjadi energi kimia dalam sejumlah molekul katalisator. Dengan sigap mereka membongkar molekul air, menghasilkan oksigen (O2) yang dilepas ke udara dan atom hidrogen bebas yang siap menjalani reaksi lanjutan.
Di saat bersamaan, stomata daun membuka tutup seperti pintu mal, untuk memastikan bahwa karbon dioksida (CO2) dari udara masuk dalam rangkaian reaksi dalam jumlah yang tepat. Dalam sel-sel daun itu pula, katalisator dan hidrogen bebas menggandengnya. Reaksi kimia berlangsung lagi, kali ini tanpa melibatkan energi matahari.
Dalam kecepatan yang juga luar biasa, reaksi kedua ini (disebut fotositesis gelap) menghasilkan senyawa organik tingkat pertama, C-H-O, dengan tiga atau empat karbon, yang menjadi bahan dasar organik yang lebih stabil: gula atau lemak.
Begitulah dedaunan menjalankan tugas sejak fajar menyingsing hingga matahari terbenam. Hasilnya, bahan organik berlimpah, bahkan melampaui kebutuhan rantai makanan itu sendiri. Proses dekomposisi oleh segala macam mikroba tak membuat seluruh limbah bahan organik itu habis. Nyatanya, terbentuklah lapisan organik dalam tanah, muncul lahan gambut, dan deposit organik lainnya. Semuanya masih menyimpan energi kimia yang asal-muasalnya dari cahaya matahari.
***
Planet bumi pun menjalani evolusinya sendiri sejak tercipta oleh ledakan besar, Big Bang, sebagai gumpalan gas, 6 milyar tahun lalu. Bumi mendingin dan memadat. Daun pertama, juga makhluk pertama di bumi ini, lahir dalam bentuk sel-sel tunggal berklorofil, 2,4 juta tahun lalu. Ia berevolusi seiring dengan evolusi geologi bumi itu sendiri. Bahkan, menurut para ilmuwan, 350 juta tahun silam muncul hutan raya generasi pertama di muka bumi ini.
Evolusi bumi berjalan, diwarnai pelbagai peristiwa geologis yang mendeformasi lapisan bumi. Lempeng-lempeng bergeser, naik dan turun. Di banyak tempat, hutan dan belukar terkubur batuan. Selama berjuta tahun di sana, dengan pemanasan sekitar 82 derajat celsius, bahan organik di kedalaman 2.500 meter itu berubah menjadi minyak. Yang terjerat lebih dalam, sampai 5.000 meter, dengan pemanasan sampai 154 derajat celsius, berubah bentuk menjadi gas. Dalam perkembangannya, minyak dan gas bumi itu cenderung mengalir dari tempat semula dan terjebak di dalam patahan-patahan lapisan bumi.
Toh, masih banyak material organik yang terserak begitu saja di dekat permukaan bumi. Mereka juga mengalami proses sendiri, melapuk, memfosil menjadi batu bara.
Bukti arkeologis menunjukkan bahwa para tentara pendudukan Romawi di Inggris telah membakar batu bara pada abad kedua dan ketiga Masehi. Penemuan mesin uap pada awal Revolusi Industri membuat pembakaran batu bara melonjak. Minyak bumi sendiri kali pertama diproduksi sebagai komoditas di Titusville, Pennsylvania, Amerika Serikat, 1959, oleh Edwin L. Drake. Dalam waktu singkat, dia menjadi kalori yang menggerakkan peradaban. Belakangan, gas bumi disedot pula sebagai sumber energi.
***
Hanya kurang dari 150 tahun, menurut Jeremy Leggett, dalam bukunya, Half Gone (2006), 920 milyar barel minyak bumi ludes dipompa dari perut bumi. Ia lebih percaya pada angka 780 milyar barel sebagai angka cadangan yang masih tersisa, ketimbang 1.147 milyar barel deposit seperti yang sering disebut para juragan minyak bumi. Namun, sekiranya angka 780 milyar barel itu benar, itu pun cukup untuk membuat atmosfer bumi bertambah buruk karena penumpukan residu CO2 dari proses pembakarannya. Belum lagi residu dari pembakaran batu bara dan gas.
Padahal, sejak akhir abad ke-19 silam ilmuwan Swedia, Svante Arrhenius, mewanti-wanti dunia industri supaya menahan diri dalam mengonsumsi bahan bakar fosil. Pemakaian yang berlebihan akan membuat CO2 menumpuk di udara dan menyebabkan pemanasan global. Toh, baru 20 tahun terakhir masyarakat dunia serius mencari jalan untuk mereduksi emisinya karbonnya. Bahkan baru 10 tahun belakangan langkah-langkah nyata mitigasi (penanggulangan) dilakukan, dengan atau tanpa kesertaan Amerika Serikat, negara yang paling rakus mengonsumsi bahan bakar fosil tapi bersikeras menolak mengurangi emisinya.
Pelbagai skema pun dijalankan. Ada kecenderungan, di negara-negara maju, pemakaian bahan bakar fosil kini semakin efisien. Tapi itu semua tidak cukup untuk menahan kenaikan konsentrasi CO2 dan gas-gas lain yang menimbulkan efek pemanasan global. Maka, salah satu agenda Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim Ke-13 di Bali, 3-14 Desember ini, adalah menelurkan protokol baru untuk memanfaatkan hutan-hutan tropis sebagai gudang penyimpanan CO2.
Dalam skema sebelumnya, hal-ihwal pengaturan pemanfaatan hutan tadi dianggap belum cukup memadai. Padahal, dengan keajaiban di dedaunannya, kawasan hutan, seperti halnya lautan, diyakini akan banyak memberi kontribusi dalam mitigasi melawan pemanasan global.
Hutan pun kembali menjadi sorotan, juga harapan. Bisakah hutan menyelamatkan dunia dari gejala perubahan iklim? Mampukah dedaunan hutan itu menyerap habis gas CO2 yang disemburkan jutaan cerobong pabrik, ratusan juta knalpot mobil dan sepeda motor, ribuan pembangkit listrik (yang memakai bahan bakar minyak, gas, atau batu bara)? Belum lagi ribuan sumber emisi karbon lainnya.
Di atas kertas, jelas hutan akan kewalahan menghadapi tugas berat itu. Menanti keajaiban baru bahwa hutan akan beradaptasi dengan lingkungan baru yang lebih sarat CO2, dengan menambah kemampuannya menyerap gas-gas tersebut, tak kunjung muncul. Penelitian Chantal D. Reid, ahli fisiologi tumbuhan di Duke University, Amerika Serikat, selama empat tahun atas 15 jenis tumbuhan menunjukkan bahwa penambahan kadar CO2 di udara mempengaruhi frekuensi stomata membuka dan menutup. Daun tak bisa serta-merta menelan CO2 lebih besar hanya karena gas tersebut tersedia lebih banyak.
Keajaiban daun barangkali hanya sebatas menyiapkan kalori bagi kehidupan bumi ini. Proses evolusi daun tidak sempat melewati tahap perubahan drastis atas komposisi atmosfer hanya dalam tempo 150 tahun. Emisi berlebihan bukanlah tanggung jawab dedaunan hutan atau plankton di lautan. Bagaimana pula kita bisa menyerahkan urusan mitigasi pada hutan dan lautan bila di antara kita sendiri ada yang tak sudi mereduksi pencemarannya? Mitigasi hendaknya berangkat dari kesediaan umat manusia sendiri untuk mengendalikan diri.
Putut Trihusodo
[Mukadimah, Gatra Edisi Khusus Beredar Kamis, 22 November 2007]