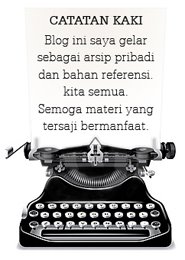Putut Trihusodo
Para nelayan itu hanya bisa bergumul dengan laut. Namun sesungguhnya mereka tak benar-benar memiliki akses pada kekayaan laut. Kapasitas teknologi yang ada pada mereka jauh dari memadai. Maka, kalaupun Indonesia mencatat produksi ikan laut 4,4 juta ton, sebagian masuk ke perut kapal-kapal tangkap milik cukong asing yang beroperasi dengan bendera Merah-Putih.
LAUT kita adalah sawah ladang yang sungguh tak terkira nilainya. Tanpa harus mencangkul dan membajaknya, kita bisa memanen hasilnya kapan kita suka. Laut pun tak meminta pupuk atau obat-obatan pengusir hama. Tak ada kata paceklik. Sekiranya kita punya teknologi dan modal, musim barat atau musim timur bukan halangan. Sekiranya kita punya pengetahuan, tidak sulit kita mencari haluan untuk menebar jaring.
Luas laut kita tak kurang dari 4 juta kilometer persegi. Menjadi 5,8 kilometer persegi jika kita mau sedikit bersusah payah melayari zona ekonomi eksklusif. Potensi lestari ikan di sana tidak kurang dari 6,4 juta ton per tahun. Kalau saja nelayan kita sanggup menangkap separuh saja, dan menjualnya dengan harga Rp 15.000 per kilogram, rezeki dari laut ini akan mencapai Rp. 46,5 trilyun. Angka itu boleh jadi berlipat, mengingat harga ikan kerapu bebek di Singapura, misalnya, bisa mencapai S$ 95 (sekitar 570.000) dan kerapu sunu S$ 32 (sekitar Rp 186.000). Bahkan kakap merah yang bukan jenis ikan gedongan bisa laku Rp 36.000 per kilogram.
Ironisnya, dari tahun ke tahun, nelayan kita tetap saja tertinggal, rombeng, compang-camping. Desa nelayan identik dengan kantong kemiskinan. Survei oleh tim Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005, sebelum harga BBM menjulang naik, menunjukkan porsi keluarga miskin di desa pesisir Jawa Timur mencapai 33,8%, dua kali rata-rata angka kemiskinan nasional. Bahkan, di pesisir Kabupaten Trenggalek, angka keluarga papa itu mencapai 58,3%, dan di Sumenep 52,1%.
Para nelayan itu hanya bergumul dengan laut. Namun sesungguhnya mereka tak benar-benar memiliki akses pada kekayaan laut. Kapasitas teknologi yang ada pada mereka jauh dari memadai. Maka, kalaupun Indonesia mencatat produksi ikan laut 4,4 juta ton, sebagian masuk ke perut kapal-kapal tangkap milik cukong asing yang beroperasi dengan bendera Merah-Putih. Kalau saja kapal-kapal durjana itu bisa kita halau, dan nelayan nasional diberdayakan, masih ada dua juta ton ikan segar lagi yang dapat kita panen setiap tahun.
Laut kita adalah sawah ladang yang tak pernah kering. Sejauh kita tidak tamak menggarapnya, ia akan menjadi harta pusaka yang abadi, yang terus akan memberi manfat buat anak-cucu, cicit, canggah, gantung siwur, dan seterusnya. Laut adalah sumber daya yang renewable, terbarukan.
Minimnya kapasitas teknologi yang dimiliki nelayan dan juragan-juragannya kadang membuat mereka menjadi zalim. Mereka menggarap harta pusaka itu dengan cara-cara teroris: bom! Natrium klorat dicampur posfat dalam adonan, diberi sumbu detonator, lalu buum! Begitulah, sebagian nelayan kita mengambil jalan pintas untuk mendapatkan kerapu bebek atau ikan napoleon. Terumbu karang hancur lebur bersama ikan-ikan yang bersarang di habitat itu. Siapa peduli.
Kemiskinan memang mudah menggoda nelayan kita menjadi ''teroris'' laut. Mereka begitu lama hidup dalam sistem ekonomi yang menekan. Rentenir lebih mereka kenal ketimbang teller bank atau ATM. Investasi adalah hal mewah yang tidak pernah mereka sentuh. Selama pemerintahan Orde Baru, investasi domestik di sektor perikanan (kelautan ada di dalamnya) cuma 1,4%. Sangat jomplang dibandingkan dengan industri yang meraup 68,7%. Investasi asing sama saja. Tanpa insentif, tanpa komitmen, tak ada investasi.
Pasca-Orde Baru, pemerintah lebih punya visi kelautan. Sejak pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, muncul Departemen Kelautan. Negara pun menoleh ke laut. Namun tak kunjung hadir langkah kongkret untuk memberdayakannya hingga kini. Investasi ke sektor laut masih terseok-seok. Perlu affirmative policies dan affirmative actions untuk sektor yang masih tertinggal ini. Situasi tak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Laut jangan lagi menjadi anak tiri yang dibiarkan hancur, tercemar, terjarah, dan tidak terurus. Sudah saatnya laut menjadi prioritas. Pemberdayaan laut tak hanya menolong nelayan miskin. Lebih dari itu, dari sana juga akan muncul permintaan tenaga kerja. Apalagi, laut kita tidak hanya memberi ikan. Di sana ada juga minyak, gas bumi, mineral, pasir, dan kekayaan biota lainnya, semisal rumput laut. Di situlah diperlukan kebijakan yang terfokus, agar pemanfaatan sumber daya itu tak mengusik satu sama yang lain yang bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem.
Di atas laut terhampar banyak kesempatan. Di pesisir laut, terbentang 1,2 juta hektare lahan yang cocok untuk tambak udang, dan baru diusahakan 350.000 hektare. Hasil tambak kita rata-rata baru 0,6 ton udang per musim. Bayangkan bila kita memiliki sejuta hektare tambak udang dengan produksi rata-rata 2 ton. Itu sama sekali tidak mustahil.
Kekayaan biodiversitas perairan pun luar biasa. Perairan Kepulauan Derawan. Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, misalnya, menyimpan 872 spesies fauna air. Mungkin saja sebagian dari mereka bisa ekonomis untuk dibudidayakan. Derawan sendiri memiliki pesona laut luar biasa, tak kalah dari The Great Reef di Queensland, Australia, tempat tujuan wisata dunia yang menghasilkan US$ 2 milyar pada 2002.
Pantai-pantai indah dan perairan yang eksotik bertebatan di Indonesia. Jangan hanya sebut Bunaken, karena masih ada kawasan seperti Derawan, Pulau Tukang Besi di Buton, Pulau Padaido (Biak), Pulau Ranca-Komodo, dan masih banyak lagi yang mendapat indeks di atas 31 atas keelokannya dari World Tourism Organization. Padahal, indeks untuk Great Reef hanya 28, Karibia 25, dan Tahiti cuma 21.
Edisi khusus Gatra kali ini membedah potensi sumber daya laut kita, dengan segala macam problemnya, mulai aspek kesejarahan teritorinya, kebijakan kelautan kita, nasib nelayan, bisnis-bisnis yang bermain di lahan basah ini, hingga persoalan konservasi serta upaya pengamanannya. Laut masih menjadi potensi yang belum tergarap secara memadai. Mari kita berlayar.
Gatra, 2 Januari 2006
Menoleh ke Laut
Senin, 02 Januari 2006
Langganan:
Komentar (Atom)