Putut Trihusodo
Setiap kali lampu-lampu hias mulai berpijar; bendera dan umbul-umbul warna-warni berkibar (oleh tiupan angin kemarau Agustus yang kering dan berdebu), ada dua butir kata yang mengusik benak kita: negara dan kemerdekaan. Adakah keduanya masih menjadi mantra sakti, yang bisa membuat kita duduk tenang memikirkan persoalan bersama?
Mungkin sebagian dari kita memilih untuk memaknainya sebagai ritual tahunan. Toh, negara yang kini menginjak usia 61 tahun ini tak kunjung "memerdekakan" mereka dari impitan hidup yang terus menekan hari demi hari. Negara cuma menjadi alamat tujuan saat mereka kandas terdeportasi sebagai tenaga kerja ilegal; atau tempat yang menyediakan kubur bagi yang gugur diterjang bom di Lebanon --ketika berjuang demi asap dapur keluarga.
Sebagian dari kita juga memaknai kemerdekaan dan negara ini cukup dengan lampu hias dan umbul-umbul. Urusan mereka dengan negara hanya sebatas surat izin ini-itu, membayar pajak bumi dan bangunan, PPh, PPN, retribusi, sumbangan, dan semacamnya. Tak usah pula sebut-sebut lagi kata mutiara ala John F. Kennedy --''Jangan tanyakan apa yang diberikan negara padamu, tapi apa yang kamu berikan padanya". Itu terlalu gombal, bahkan untuk dipidatokan sekalipun.
Barangkali kita selama ini terlalu sibuk dengan urusan masing-masing hingga tak sempat bekerja sama memberikan makna lebih dalam mengenai negara dan kemerdekaan. Kita tahu, negara cuma sebuah kata abstrak yang tak memberikan apa-apa bila kita sendiri tak mengisinya dengan kerja sistematis yang terus-menerus tanpa batas waktu.
Mungkin sebagian dari kita sudah merasa bekerja keras. Tapi mungkin tidak terlalu keras dan tak pula cukup sistematis. Apa pun, kita sama-sama tahu, hasilnya masih jauh dari harapan tentang negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah....
Daya Saing
Yang kita saksikan selama ini adalah kisah-kisah tragis, ironis, atau apa pun yang bisa menggerogoti kebanggaan kita. Bahkan makin banyak dari kita kehilangan simbol-simbol kebanggaan, pamor, dan mungkin juga sebagian daya tahan.
Daya saing kita sebagai satu masyarakat telah pula merosot. Institute of Management Development (IMD), lembaga pendidikan yang berwibawa di Jenewa, menempatkan daya saing kita di posisi ke-60 pada 2006. Turun satu tangga dari tahun sebelumnya. Di bawah kita ada Venezuela. Namun negeri jiran Malaysia bisa mendaki ke posisi 23, Thailand 32, dan Filipina 49. Singapura, seperti biasa, ada di peringkat atas, yakni posisi ketiga di bawah Hong Kong (2) dan Amerika Serikat (1).
Pemeringkatan itu muncul dalam laporan survei bertajuk ''The World Competitiveness Scoreboard 2006''. IMD secara rutin melakukannya. Hasilnya, daya saing Indonesia di tahun 2000-an ini bertengger pada posisi sekitar 60. Sebaliknya, Singapura hampir tak pernah keluar dari posisi lima besar.
Peringkat yang relatif tinggi memang tak serta-merta menunjukkan sebuah negeri itu mapan dan makmur. Sebaliknya, yang posisinya rendah tak berarti miskin. Italia, sebagai misal, ada di peringkat ke-56 (2000). Namun peringkat ini menunjukkan berapa besar peluang sebuah negara menambah kapasitas ekonominya. Dengan bercokol di posisi rendah, jelas Indonesia bukan negara yang dilirik untuk kerja sama ekonomi.
Dalam menyusun peringkat daya saing itu, IMD bersandar pada 95 butir kriteria, yang kemudian diperas menjadi lima. Ada kriteria keilmuan, yang di dalamnya antara lain ada unsur sumber daya manusia, kapasitas riset, dan kemampuan menciptakan produk orisinal. Lantas ada kriteria lingkungan hidup dan kesehatan, pendidikan, teknologi, serta infrastructure basic. Termasuk yang terakhir (dari 22 kriteria) antara lain sumber daya alam, rel kereta api, jalan raya, dan harga listrik. Output dari kelima hal tadi berupa daya saing.
Banyak lembaga manajemen mengeluarkan survei serupa, dan ujung-ujungnya selalu menempatkan Indonesia di posisi yang jauh dari posisi terhormat. Kita memang bisa bicara tentang banyaknya cerdik pandai di sekitar kita, banyaknya anak berbakat, juga kekayaan alam yang melimpah dan posisi geografis yang penting. Mestinya, tinggal buka pintu, orang akan datang, lalu menawarkan pelbagai kerja sama. Tapi kita tahu, hal itu tidak pernah terjadi. Mengapa bisa begini?
Yang paling mudah adalah mencari kambing hitam. Kita bisa mengumpat kiri-kanan, menyalahkan kekuasaan, menghujat aparatur negara, mencela pengusaha, atau sekadar mengecam tatanan global. Namun sekadar mencela tanpa iktikad membangun suatu proses dialektika tak membuat kegagalan menjadi sebuah pelajaran. Sejarah nasional kita terpampang panjang di belakang. Mestinya sudah banyak pelajaran penting yang bisa kita tarik dari sana. Yang kita perlukan barangkali kejujuran dan kearifan untuk menarik hikmah dari sejarah.
Simbol Kebanggaan
Mungkin kini saatnya kita lebih rendah hati. Tak perlu lagi mencurigai sebuah kekuasaan sebagai hal yang seram mengancam. Ia perlu ruang untuk bergerak efektif. Belakangan kita diyakinkan, sekurangnya oleh filsuf Prancis Michel Foucault, bahwa kekuasaan pun membawa hal-hal yang konstruktif. Foucault menolak anggapan kaum strukturalis yang sering menggambarkan kekuasaan dari sisi kebuasannya. Kuasa bisa memberikan pengetahuan, kata Foucault, meski itu terkait dengan kepentingan kuasa itu sendiri.
Dalam konteks inilah kita bisa mengingat sosok Bung Karno, yang kuasanya memberi pengetahuan bagi kita bahwa betapa gelora nasionalisme yang ia kembangkan dapat menghimpun segala potensi negeri untuk kemudian berderap serempak. Masih segar dalam ingatan kita, betapa doktrin stabilitas dan konsistensi kebijakan di era Presiden Soeharto memberi peluang bagi banyak kegiatan ekonomi.
Namun, dari kedua pemimpin itu, kita juga bisa belajar perlunya kekuasaan itu dapat bersikap rendah hati agar amanah. Kondisi ini diperlukan agar ia tumbuh jadi sebuah kekuasaan yang efektif dan kokoh untuk mengorganisir segala potensi negeri ini. Kita memerlukan kondisi itu untuk membangun daya saing baru, sekaligus menghadirkan simbol-simbol kebanggaan baru bagi warga negara.
Di masa lalu, kita cukup bangga hanya dengan mendengar orasi tentang Indonesia adalah negeri zamrud khatulistiwa. Kita memerlukan simbol kongkret yang tidak saja memberikan kebanggaan, juga mengangkat martabat kehidupan rakyat. Ia bisa jadi sebuah ikon nasional yang mengakar pada perasaan publik secara luas.
Untuk simbol yang menjadi kebanggaan nasional, menjadi pengikat keutuhan bangsa, dalam orasinya di pelbagai kesempatan, Bung Karno menyebutnya sebagai ''tali jiwa". Kita memerlukan tali jiwa baru.
Pada edisi khusus 17 Agustus 2006 kali ini, Gatra mencoba menghadirkan sejumlah individu, karya, juga kekayaan alam yang berpotensi menjadi "tali jiwa" baru. Beberapa individu kami hadirkan untuk mewakili sekelompok intelektual yang mencoba mencari jalan guna mengembangkan potensi dan kekayaan alam yang ada. Sebagian lainnya mencoba membuat terobosan agar kerumitan yang ada menjadi lebih sederhana penanganannya.
Kami hadirkan pula produk-produk yang, betapapun sederhana, telah memberi arti bagi perekonomian kita. Mereka mampu bersaing di era serba bebas. Di bagian akhir edisi khusus ini, kami hadirkan potensi sumber daya alam yang tersisa, yang ternyata masih sangat berharga.
Edisi khusus Gatra kali ini hanya mencoba mengingatkan bahwa kita masih punya tali jiwa. Kita hanya perlu merajutnya lebih jauh agar ia bisa menjadi pengikat bagi jiwa nasionalisme kita di tengah gelora globalisasi ini.
Gatra, 14 Agustus 2006
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

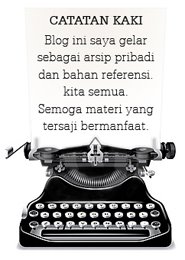
0 komentar:
Posting Komentar