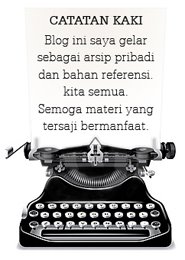Putut Trihusodo
Gempa bumi adalah salah satu tragedi paling seram di antara bencana alam lainnya. Daya rusaknya yang massif hampir selalu melahirkan kisah dramatis. Di era informasi kini, peristiwa gempa cepat tersebar ke khalayak lewat siaran radio, tayangan televisi, dan media cetak. Tragedi yang ditimbulkannya pun lalu menghantui publik melampaui magnitude getarannya sendiri.
Dari segi geofisika, gempa itu sendiri merupakan peristiwa alam biasa, tak beda dengan hujan badai, angin musim, dan ombak di laut. Toh, gempa menjadi momok yang lebih menakutkan karena kehadirannya yang selalu tak terduga. Kita tidak tahu persis kapan dan bagaimana ia akan datang. Apa pun, ia bagian dari kehidupan manusia, utamanya di bagian bumi yang sering menjadi lintasan gempa, termasuk di sebagian kepulauan Nusantara.
Maka, gempa bumi menjadi kosakata di banyak tempat. Dalam bahasa Arab klasik ada kata zilzal yang merujuk ke gempa. Orang Cina Selatan menyebutnya ti chan. Di Meksiko dan negara Amerika Tengah lainnya, orang menyebut temblor untuk gempa. Orang Jawa (juga Palembang) menjulukinya lindu. Dalam bahasa Sunda, ia disebut lini. Orang Toba melafalkannya sebagai suhul. Kata ''gempa'' ada di hampir semua bahasa di dunia.
Sebaran gempa bumi sendiri memang sangat luas, meski kejadiannya lebih banyak mengikuti busur ring of fire, mulai pantai selatan Indonesia, ke Filipina, Jepang, Alaska, Amerika Serikat, Meksiko, hingga pesisir barat Amerika Latin.
Dinamika lempeng bumi, patahan, sesar, palung, dan potensi vulkanik yang memicu gempa itu begitu aktif sehingga gempa, besar atau kecil, hampir terjadi tiap hari. Catatan US Geological Survey menunjukkan bahwa lindu ringan (light), yang berkekuatan 4-4,9 pada skala Richter, rata-rata terjadi 13.000 kali per tahun alias 35,6 kali sehari. Yang berkekuatan moderate, 5-5,9 skala Richter, rata-rata 1.319 kali per tahun atau 3,6 kali per hari!
Gempa kuat (strong), 6 hingga 6,9 skala Richter, juga kerap terjadi di dunia ini. Rata-ratanya 134 kali per tahun atau sekali tiap tiga hari. Yang lebih dahsyat, major earthquake, 7-7,9 skala Richter, rata-rata 17 kali per tahun. Sedangkan great earthquake yang ber-magnitude 8 skala Richter ke atas terjadi sekali dalam setahun.
Kenaikan satu pada skala magnitude gempa, menurut US Geological Survey, membawa konsekuensi besar, yakni mengakibatkan ground motion change yang 10 kali lebih kuat karena pelepasan energi (hasil lentingan lapisan bumi) yang 32 kali lebih besar.
Amerika Serikat sendiri adalah satu negara yang sering berurusan dengan gempa. Pada tahun 2000 hingga 20005, di sana terjadi lima kali gempa berkekuatan 7-7,9 skala Richter. Tiga kali di antaranya terjadi di kawasan Alaska. Pada periode yang sama, gempa kuat (6-6,9 skala Richter) terjadi 33 kali.
Dilihat dari sisi statistik, gempa bumi susul-menyusul yang menerpa Indonesia pun mestinya bisa dimaklumi. Seperti halnya Amerika Serikat, Filipina, Meksiko, dan Jepang, bumi Nusantara ini bertumpu di atas lempengan yang tidak stabil. Gempa adalah konsekuensi yang harus dihadapi.
Persoalannya, kita belum mampu keluar dari trauma gempa dan gelombang tsumami Aceh, 26 Desember 2004, dengan korban tewas dan hilang lebih dari 170.000 jiwa, yang disusul dengan gempa yang menimpa Pulau Nias pada Maret 2005, lalu gempa Yogyakarta pada Mei 2006 (lebih dari 5.000 jiwa melayang), gempa pantai selatan Jawa (lebih dari 600 jiwa tewas), kemudian guncangan bumi yang terasa di Gorontalo dan Singaraja.
Statistik dan teori-teori geofisika memang dapat menjelaskan fenomena alam tadi. Namun trauma beruntun bisa membuat orang sulit mencernanya. Jangan heran bila sebagian dari kita mencari ''penjelasan'' lain lewat pendekatan kosmologi, ngelmu, yang tak banyak mendapat perhatian dalam dunia sains. Di bawah "teori" kosmologi, bencana alam lalu dikait-kaitkan dengan masalah politik kekuasaan.
Seperti halnya gempa dan fenomena alam lainnya, kosmologi dan penganutnya juga sebuah fakta yang ada di lapangan. Kita membuang waktu bila harus berpretensi menghapusnya. Akan lebih baik bila wacana dialihkan pada aspek mitigasi bencana alam itu sendiri. Mitigasi yang baik mungkin bisa membantu mempercepat luka atas trauma. Setidaknya, itu akan membawa kita ke alam dan membangun harapan-harapan baru yang masuk akal.
GATRA, 24 Juli 2006
Gempa 3,6 Kali Per Hari
Sepak Terjang Teroris di Mata Polisi
Putut Trihusodo
Aksi terorisme agama ternyata tak segencar teror separatisme atau komunisme. Tidak ada konspirasi dalam penanganan kasus bom Bali. Polri bekerja berdasarkan forensik.
RESENSI
TERORISME, MITOS DAN KONSPIRASI
Penulis: Budi Gunawan
Penerbit: Forum Media Utama, Juni 2006, 334 halaman
Sepanjang tahun 2000 hingga 2005, tak kurang dari 20 kali teror bom terjadi di wilayah hukum Indonesia. Korban jiwa secara langsung 287 orang dan ratusan lainnya mengalami cedera. Kehadiran terorisme di Indonesia benar-benar nyata dan ancamannya belum berakhir. Noor Din Mohd. Top masih gentayangan dan terus menyelinap lolos dari kejaran polisi.
Kelompok Noor Din Mohd. Top ini, dalam catatan versi Departemen Pertahanan Amerika Serikat, hanya satu dari 43 kawanan teroris yang beroperasi di Asia Tenggara dan Oseania. Ia juga hanya satu dari 967 kelompok teroris di dunia. Sarang teroris terbesar ternyata di Eropa Barat (267), kemudian Timur Tengah (192), Asia Selatan (131), dan Amerika Latin-Karibia (110).
Dalam bab pertama dan kedua, Budi Gunawan mencoba menggali sejarah ringkas batasan tindakan terorisme itu. Secara klasik, teror sering didefinisikan sebagai aksi keji untuk menimbulkan rasa takut luar biasa untuk memaksakan kehendak. Bila ini yang menjadi acuannya, maka teror negara termasuk di dalamnya. Maka, terorisnya, ya, mulai Stalin, Lenin, Hitler, hingga Mao. Mengutip tulisan Noam Chomsky, penulis menyatakan pula bahwa Amerika Serikat menjalankan terorisme atas negara-negara lemah.
Budi Gunawan mengakui, sejauh ini belum tersedia jawaban memuaskan atas pertanyaan apa dan siapa terorisme itu (halaman 26). Maka, dalam bab-bab lanjutannya, sebagai polisi, Budi memilih mengacu pada dokumen dan produk hukum positif yang ada, baik secara domestik maupun internasional --semisal Statuta Roma. Nah, dari sini kemudian terorisme itu menunjuk pada kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan terhadap penduduk awam untuk memaksakan gagasan.
Mereka bangkit dari pelbagai kelompok ide. Ada teroris antiglobalisasi, teroris pro-komunis, teroris perjuangan lingkungan hidup, agama, ras, separatis, dan seterusnya. Dalam sejarahnya, kelompok teroris agama itu bukan yang dominan. Teroris agama (termasuk Al-Qaeda dan Tentara Republik Irlandia) "cuma" melakukan 1.925 kali kekerasan. Angka ini jauh di bawah aksi teroris separatis (3.966) dan teroris komunis (3.179).
Sebelum masuk membahas terorisme Indonesia lebih jauh, Budi --brigadir jenderal polisi yang produktif menulis dan kini menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier pada Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri-- sempat pula membahas urusan agama dan terorisme. Sorotannya lebih pada soal ideologi yang disebutnya sebagai sistem tata nilai yang "cacat sejak lahir" (congenital defect) dengan karakternya yang selalu membenarkan diri sendiri (halaman 60).
Toh, Budi perlu juga membahas dan membantah ideologi jihad seperti yang dianut Imam Samudra. Dalam satu bab, ia mengutip pelbagai sumber untuk menunjukkan adanya pemahaman lain bahwa jihad yang dilakukan Imam Samudra cs tidak sesuai dengan Islam. Memang, apa yang disampaikannya pada bab ini bukan hal baru. Tampaknya ia ingin melengkapi bukunya agar lebih konprehensif.
Yang menarik pada buku ini adalah tiga bab terakhir yang menyoroti terorisme di Indonesia. Satu hal yang dikupasnya ialah kurang antusiasnya dukungan publik terhadap langkah pencegahan dan penanganan terorisme. Upaya penanggulangan, termasuk penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, diopinikan seolah semata-mata karena tekanan internasional.
Ketika perpu itu berkembang menjadi Undang-Undang Nomor 16/2003, persoalan baru pun muncul lagi. Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan undang-undang itu karena sengketa soal prinsip retroaktifnya. Nasib keputusan MK itu kini tak jelas.
Budi Gunawan menutup bukunya dengan penolakan dia terhadap spekulasi adanya konspirasi di balik pengungkapan kasus bom Bali. Sukses Polri adalah semata-mata karena cermat mengikuti prosedur dan kaidah forensik. Tidak ada urusan dengan Amerika Serikat atau kepentingan global. Ia juga mempertanyakan selera pers yang gencar mengulas pelbagai teori konspirasi yang bukti-buktinya di lapangan ternyata nihil.
Buku Terorisme, Mitos dan Konspirasi ini terkesan kurang dalam, kurang fokus, dan kurang tuntas. Namun ia bisa menjadi referensi berharga di tengah ketiadaan buku yang membahas terorisme domestik.
GATRA, 24 Juli 2006
Derita Lebanon
Putut Trihusodo
Orang Lebanon tak suka berperang. Mereka lebih berminat ke bisnis, intelektual, seni budaya, dan tak pernah membangun militer yang kuat. Namun mereka harus hidup di kawasan yang panas, utamanya karena bara zionisme.
Jerih payah selama 16 tahun rontok dalam sekejap. Begitu nasib Lebanon kini. Sejak 1990, setelah dilanda konflik bersenjata selama 15 tahun, negeri cantik di tepi Laut Mediterania itu bangkit dari puing-puing keruntuhannya. Gedung perkantoran, jalan raya, hotel-hotel, apartemen, jembatan, bandara, pembangkit listrik, dan infrastruktur lainnya dibangun. Institusi pemerintahan berdenyut kembali.
Pamor Lebanon pun tumbuh hampir pulih. Ibu kota Beirut mulai berbinar. Predikat ''Paris of Middle East'' kembali disandangnya. Badan-badan PBB, semisal ILO dan UNESCO, membuka perwakilannya untuk kawasan Arab di Beirut. Turis asing juga membanjiri Lebanon. Tahun lalu, jumlahnya 1,6 juta.
Pelbagai infrastruktur terus dibangun. Maklum, Beirut menjadi salah satu kandidat tuan rumah Olimpiade musim panas 2024. Yang sudah dekat adalah tuan rumah bagi event ''Jeux de la Francophonie 2009'', sebuah pesta olahraga negara-negara berbahasa Prancis. Di negeri ini, bahasa Prancis adalah yang kedua setelah bahasa Arab.
Jerih payah selama 16 tahun itu telah memberi hasil kongkret. Beirut tumbuh jadi sebuah kota dengan atmosfer kosmopolitan. Sekitar 1,2 juta warga menghuni kota itu, dan angka itu menjadi 1,7 juta bila ditambah penduduk di pinggiran kota. Pusat bisnis, pasar modal, stasiun-stasiun TV, butik, kafe, dan mal-mal bertebaran di Beirut. Ekonomi tumbuh. Pendapatan per kapita warga Lebanon telah mencapai US$ 5.100.
Namun segala kisah sukses itu sepertinya akan rontok saat pesawat-pesawat tempur Israel secara membabi buta menyerang Lebanon, termasuk Beirut, sejak Rabu pekan lalu. Dalihnya, memerangi milisi Hisbullah yang ada di negeri itu. Gara-garanya, dua serdadu Yahudi ditangkap Hisbullah di perbatasan Israel-Lebanon.
Serangan gencar dengan roket, senapan mesin, dan bom itu meluluhlantakkan banyak target di Lebanon. Sebagian sasaran adalah kawasan yang dianggap sebagai kantong-kantong Hisbullah seperti di Dahieh, Beirut Selatan. Toh, militer Israel gatal tangan menghancurkan Bandara Rafic Hariri, pembangkit listrik, jalan raya Beirut-Damaskus, jaringan telekomunikasi, serta jembatan yang dianggap menghubungkan ke kawasan Hisbullah.
Sejak serangan pertama itu, pasar modal di Beikut tutup, setelah sebelumnya anjlok 15%. Industri pariwisata, yang diharapkan mendatangkan pemasukan US$ 2,5 milyar tahun 2006 ini, kolaps seketika. Kerugian fisik sampai pada tiga hari pertama serangan mencapai US$ 500 juta. Siapa yang bertanggung jawab?
Penduduk Lebanon kini 3,8 juta, 200.000 di antaranya migran dari Palestina. Di luar itu, 15 juta orang berdarah Lebanon lainnya hidup tersebar di pelbagai penjuru dunia. Komunitas Lebanon sendiri berdarah campuran dari suku tua Phonix, Syiria, Yunani, Roma, Arab, Kurdi, dan Prancis, yang datang bersama pasukan Salib berabad silam. Sekitar 57% adalah muslim (Suni, Syiah, Druze, dan Alawit). Selebihnya, 40%, Kristen (Katolik Maronit, Ortodoks Yunani, Katolik Armenia, dan Protestan). Di luar itu, ada segelintir Yahudi.
Meski penduduknya heterogen, sejarah mencatat, Lebanon relatif stabil. Transisi dari pemerintah kolonial Prancis ke Lebanon yang merdeka tahun 1945 berjalan tanpa gejolak. Kalaupun ada satu faktor yang membuat negeri itu gonjang-ganjing, tak lain adalah Israel dengan zionismenya. Ulah Israel pula yang membuat 300.000 warga Palestina hijrah ke Lebanon pada 1975.
Kehadiran pengungsi Palestina itu melahirkan konflik domestik yang lantas berkobar menjadi perang sipil sesama orang Lebanon, karena campur tangan tetangga, Suriah dan kemudian Israel. Selama 15 tahun, Lebanon menjadi ajang bagi ledakan bom dan letusan senapan. Tak kurang dari 100.000 orang tewas.
Orang Lebanon tak suka berperang. Mereka lebih berminat ke bisnis, intelektual, seni budaya, dan tak pernah membangun militer yang kuat. Namun mereka harus hidup di kawasan yang panas, utamanya karena bara zionisme. Sejumlah warga Lebanon pun terseret ke dalam konflik regional, seperti para milisi Hisbullah yang bersimpati pada perjuangan Palestina. Pemerintah Lebanon tidak bisa mengontrol mereka. Namun itu tak bisa jadi alasan untuk serangan membabi buta, yang tidak saja membuat kerugian besar, juga mencabik rasa keadilan.
Gatra, 17 Juli 2006
Hinterland
Singapura adalah tetangga yang kaya raya. Negeri sekepal ini sanggup memberikan kemakmuran bagi 4,3 juta penduduknya dengan standar Eropa Barat. Pendapatan per kapita penduduk Singapura saat ini US$ 28.000. Jauh berlipat melampaui tetangga terdekatnya, Indonesia.
Uang melimpah ruah di Singapura, baik itu milik negara, swasta, maupun tabungan rakyatnya. Belum lagi uang-uang titipan yang datang dari pelbagai penjuru dunia (termasuk duit yang kabur dari Indonesia) yang kini berada di tangan para fund manager yang mengoperasikan pelbagai lembaga keuangan. Singapura adalah sumber modal.
Sukses itu diraih lewat kerja keras selama empat dekade. Di bawah pemerintahan yang efektif, bersih, dan hukum yang tegak, kerja keras itu segera memberi hasil nyata. Negeri sekepal itu pun tumbuh cepat, bahkan secara fisik luas daratannya terus bertambah dari 490 kilometer persegi 30 tahun lalu menjadi 660 kilometer persegi saat ini, dengan proyek reklamasinya.
Dari Singapura, uang mengalir ke mana-mana dalam beragam bentuk investasi. Negara-negara yang relatif baru menggeliat bangkit seperti Kamboja dan Vietnam turut kebanjiran uang ''negeri singa'' itu. Ironisnya, tidak banyak yang masuk Indonesia.
Namun para pemimpin Singapura agaknya sadar, mana mungkinlah mereka bisa tidur nyenyak bila tetangga di depan pintu rumah hidup serba kesulitan. Memang tidak berarti mereka harus peduli pada kondisi Indonesia secara keseluruhan. Tapi setidaknya, daerah terdekatnya bisa didorong lebih makmur sehingga menjadi penyangga bagi "pengaruh buruk" negeri tetangga.
Boleh jadi, itu suatu hal yang mendorong Singapura tertarik dengan proposal SEZ (special economic zone). Dalam bentuk nota kesepakatan (MoU), gagasan SEZ itu diteken Pemerintah Indonesia dan Singapura pada akhir Juni lalu. Intinya ialah kehendak untuk mengembangkan daerah Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) menjadi satu kawasan industri maju.
Pertimbangan politik adalah satu hal. Namun ada hal lain, yakni daya tarik alam BBK itu sendiri. Sebagaimana Singapura, Pulau Batam, Bintan, dan Karimun yang berada di jalur urat nadi perdagangan dunia "Selat Malaka" adalah tempat-tempat yang sangat berharga secara ekonomi. Apalagi, dalam pandangan orang Singapura, tiga pulau itu ibarat hinterland, daerah pedalaman, mereka. Apa salahnya turut mengurus wilayah pedalaman?
Namun kita tahu, membangun SEZ bukan hal sederhana. Tak cukup selembar MoU. Di sana perlu kelengkapan infrastruktur dan terutama perangkat aturan main yang jelas --syukur ditambah insentif yang menarik investor. Justru dalam masalah perangkat aturan ini kita sering kedodoran.
Kita punya pengalaman dengan Batam. Di awal 1990-an, kita sempat punya harapan besar atas Batam. Pulau seluas 612 kilometer persegi itu pernah berjaya di tahun 1990-an, tapi kini pamornya sebagai pulau industri meredup. Banyak pemilik industri di Batam yang angkat kaki, memindahkan pabriknya ke Cina atau Vietnam.
Padahal, Batam sempat tumbuh pesat. Di awal 1970-an, pulau yang ukurannya tidak terpaut jauh dari Singapura itu hanya dihuni 3.000-an orang. Tiga puluh tahun kemudian, penghuninya hampir 700.000 jiwa. Pada tahun 2000, sebelum kinerjanya anjlok, Batam memberi tempat bagi 140.000 tenaga kerja sektor formal. Ratusan industri di sana juga menciptakan 8.000 unit usaha kecil dan menengah.
Batam sempat gebyar-gebyar. Investasi swasta asing dan nasional pernah mencapai US$ 6,1 milyar (2000). Nilai ekspornya US$ 6,7 milyar tahun itu. Setoran pajak ke pemerintah pusat sekitar Rp 900 milyar. Namun kesimpangsiuran aturan main membuat gemebyar industri Batam meredup, meski belum padam sepenuhnya.
Kita tahu, adanya tumpang tindih kewenangan antara Badan Otorita dan Pemerintah Kota Batam, yang lahir dari rahim otonomi daerah, menjadi satu masalah. Ketidakjelasan Batam sebagai bonded zone atau free trade zone adalah persoalan lainnya. Puncaknya ialah ketika pemerintah memberlakukan pajak pertambahan nilai dan pajak barang mewah di luar enam bonded zone yang ada.
Memang tak seluruh masalah dari kita. Pengenaan pajak itu, misalnya, adalah buah "intimidasi" Dana Moneter Internasional (IMF). Toh, muaranya satu: tidak ada konsistensi aturan. Pengalaman di Batam hendaknya memberi pelajaran bahwa SEZ harus dirancang dengan perencanaan yang matang agar aturan main tak mengalami bongkar pasang.
Putut Trihusodo
[Lensa, Gatra Nomor 35 Beredar Kamis, 13 Juli 2006]